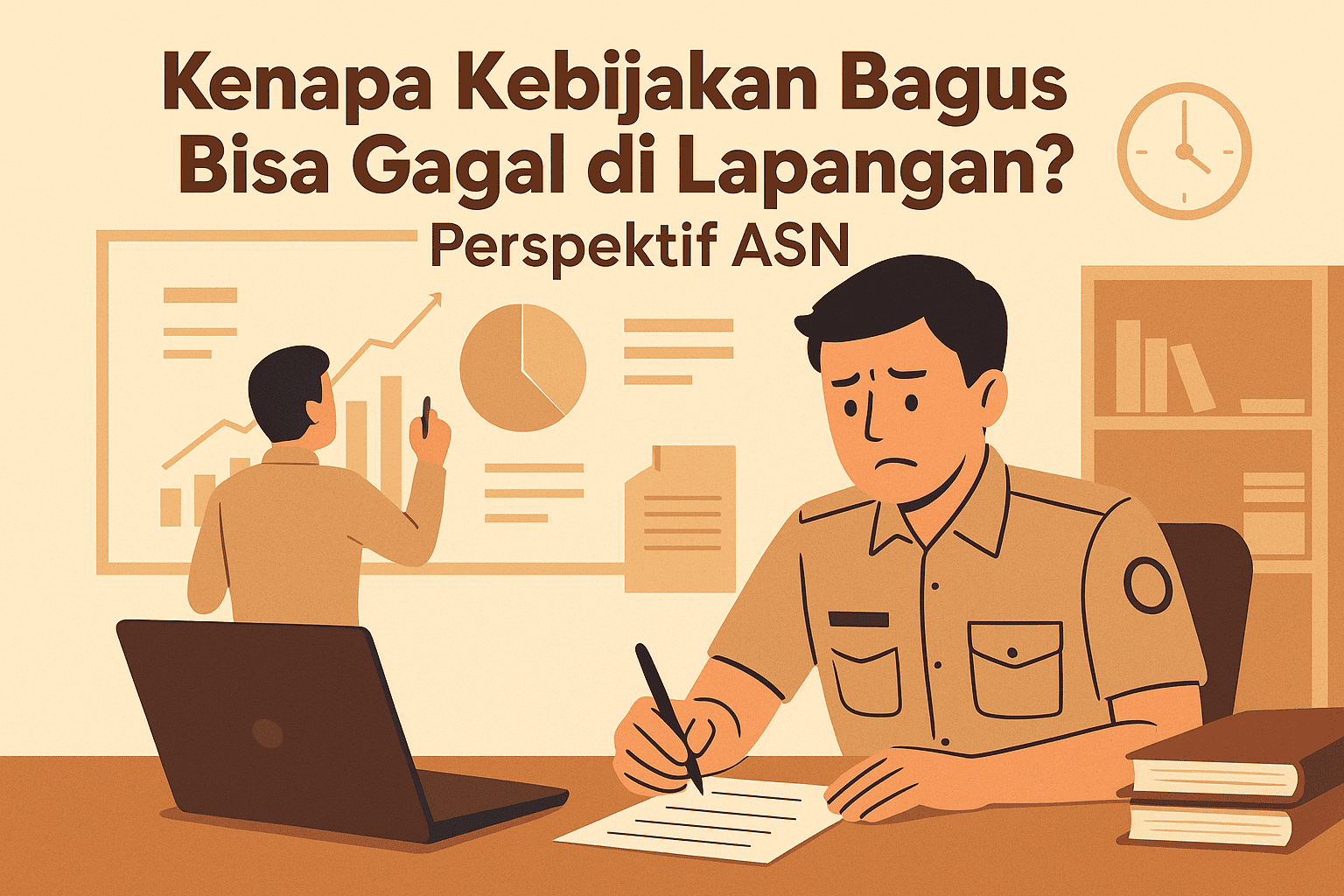
Hampir setiap ASN pernah mengalami situasi ini: sebuah kebijakan baru diumumkan dengan optimisme tinggi. Tujuannya mulia, konsepnya rapi, dan narasinya menjanjikan perbaikan layanan publik. Di ruang rapat, kebijakan itu terdengar sangat masuk akal. Namun beberapa bulan kemudian, di lapangan, hasilnya jauh dari yang dibayangkan.
Masyarakat mengeluh, pelaksana kewalahan, dan kebijakan kembali dianggap “tidak efektif”. Pertanyaannya, jika kebijakannya bagus, kenapa dampaknya sering tidak terasa?
Dari perspektif ASN yang berada di garis pelaksanaan, kegagalan kebijakan jarang disebabkan oleh niat buruk. Justru, masalahnya sering terletak pada jarak antara desain kebijakan dan realitas lapangan.
Banyak kebijakan disusun dengan asumsi kondisi ideal. Misalnya, semua daerah dianggap memiliki kapasitas sumber daya manusia yang relatif setara, akses teknologi yang memadai, dan waktu pelaksanaan yang cukup. Padahal, kenyataan di lapangan sangat beragam.
Ada unit kerja yang hanya memiliki sedikit pegawai untuk menangani banyak tugas sekaligus. Ada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, namun tetap dibebani target yang sama dengan wilayah lain. ASN pelaksana akhirnya harus “memutar otak” agar kebijakan tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan.
Di titik ini, kebijakan mulai bergeser dari tujuan awalnya. Bukan karena salah arah, tetapi karena medan yang dihadapi tidak sepenuhnya diperhitungkan sejak awal.
Di atas kertas, kebijakan biasanya dilengkapi dengan pembagian peran yang jelas. Siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Namun dalam praktik, koordinasi lintas unit atau lintas instansi sering kali jauh lebih rumit.
Perbedaan interpretasi aturan, ritme kerja yang tidak sama, hingga kepentingan sektoral membuat proses menjadi lambat. ASN di lapangan sering berada di posisi “menunggu”: menunggu arahan lanjutan, menunggu kesepakatan, atau menunggu keputusan yang tidak kunjung turun.
Akibatnya, fokus bergeser. Energi yang seharusnya digunakan untuk memastikan kebijakan berdampak ke masyarakat justru habis untuk mengelola proses internal.
Salah satu ironi birokrasi adalah keberhasilan sering diukur dari kelengkapan laporan. Selama target administratif terpenuhi, kebijakan dianggap berjalan. Padahal, angka di atas kertas belum tentu mencerminkan kondisi nyata.
ASN pelaksana memahami betul bahwa menyusun laporan sesuai format sering kali lebih “aman” daripada menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Bukan karena ingin menutup-nutupi, melainkan karena sistem penilaian belum sepenuhnya memberi ruang pada kejujuran proses.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan berisiko berubah menjadi rutinitas tahunan. Ada kegiatan, ada laporan, tetapi perubahan di masyarakat berjalan sangat pelan.
Di lapangan, ASN memiliki banyak cerita: tentang prosedur yang terlalu kaku, tentang indikator yang tidak relevan, atau tentang pendekatan yang justru lebih efektif meski tidak tertulis di pedoman. Sayangnya, cerita-cerita ini jarang naik ke level pengambilan kebijakan.
Umpan balik sering berhenti di laporan teknis atau diskusi informal. Tidak banyak ruang resmi untuk mengatakan, “Kebijakan ini baik, tapi perlu penyesuaian di sini dan di sini.” Akibatnya, kebijakan yang sama terus dijalankan dengan pola yang sama, meskipun tantangannya berulang.
Dalam kondisi seperti ini, ASN pelaksana sering berada di posisi serba salah. Jika menjalankan kebijakan apa adanya, dampaknya bisa minim. Jika melakukan penyesuaian, ada kekhawatiran melampaui kewenangan.
Pilihan paling rasional sering kali adalah pilihan paling aman: patuh pada aturan, meski hasilnya belum optimal. Ini bukan soal kurangnya kepedulian ASN, melainkan refleksi dari sistem yang masih lebih menghargai kepatuhan formal dibanding pembelajaran bersama.
Pengalaman ASN di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang baik tidak cukup hanya dirancang dengan niat mulia. Ia perlu ruang untuk diuji, dikoreksi, dan disesuaikan. Keberhasilan kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa rapi dokumennya, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Mendengar suara pelaksana bukan berarti melemahkan kebijakan, justru menguatkannya. ASN di lapangan bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan jembatan antara gagasan dan kenyataan.
Ketika kebijakan bagus gagal di lapangan, mungkin itu bukan akhir cerita. Bisa jadi, itu adalah sinyal bahwa sudah waktunya kita lebih serius mendekatkan kebijakan pada realitas.